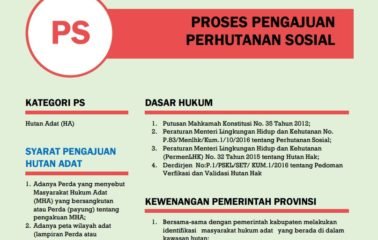Demi menyelamatkan lingkungan, mereka berani menggerakkan masyarakat untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Mereka berjuang dan bertahan meski harus bersembunyi, diancam akan dibunuh, bahkan dibuang ke tempat penampungan kotoran manusia.
1. Loir Botor Dingit
Petani rotan Dayak Bentian - Kalimantan Timur
Penerima Goldman Environmental Prize 1997
Menggerakkan masyarakat adat Dayak Bentian (laki-laki dan perempuan) untuk memperjuangkan hak-hak dasar yang dilanggar oleh korporasi kayu perusak hutan adat.
- Sejak 1986, ia bersama masyarakat adat Dayak Bentian (laki-laki dan perempuan) mengajukan petisi kepada pemerintah Indonesia tentang penerbitan sertifikat kepemilikan tanah untuk wilayah hutan adat.
- 1993: sebuah perusahaan menggusur sejumlah wilayah hutan rotan dan kuburan leluhur Dayak Bentian.
- 1994 ia memimpin masyarakat adat Dayak Bentian (laki-laki dan perempuan) untuk bertemu dengan Kementerian Transmigrasi RI di Jakarta. Hasilnya, Kementerian mengeluarkan pernyataan publik tentang perlunya menghormati hak-hak suku bangsa Kalimantan.
- 1996: Kementerian Kehutanan RI memulai proyek percontohan mengenai pengelolaan 10.000 hektar hutan oleh warga setempat (laki-laki dan perempuan).
- 1996: ia dipilih menjadi Ketua Dewan Adat Dayak Bentian.
2. Yosepha Alomang
Bidan & tokoh perempuan Amungme - Papua
Penerima Goldman Environmental Prize 2001
Mengatur perlawanan rakyat Papua (laki-laki dan perempuan) terhadap operasi tambang emas terbesar di dunia.
- Sejak kecil, ia yatim piatu dan hidup nomaden bersama penduduk desa lainnya.
- 1977: anak sulungnya yang baru berusia 3 tahun meninggal dunia akibat kelaparan.
- 1991: ia berunjuk rasa 3 hari di bandar udara Timika dengan memasang api di landasan udara sebagai simbol penolakan terhadap perusahaan asing dan protes terhadap pemerintah Indonesia.
- 1994: ia ditangkap karena dicurigai menolong tokoh Organisasi Papua Merdeka lalu dimasukkan ke tempat penampungan kotoran manusia selama seminggu.
- 1996: ia mengajukan tuntutan perdata terhadap perusahaan Amerika Serikat dan menuntut ganti rugi untuk warga masyarakat (laki-laki dan perempuan) dan kerusakan lingkungan.
- 1999: ia menerima penghargaan Yap Thiam Hien dari Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- 2001: ia mendirikan Yayasan Hak Asasi Manusia Anti Kekerasan (YAHAMAK).
- 2001: ia menggunakan uang ganti rugi perusahaan Amerika Serikat untuk membangun klinik, gedung pertemuan, panti asuhan anak yatim, dan monumen pelanggaran HAM.
3. Samuel Oton Sidin
Pastor - Pontianak, Kalimantan Barat
Penerima Kalpataru 2012 kategori Pembina Lingkungan
Menggagas dan mengelola kawasan pelestarian lingkungan melalui pendekatan keagamaan.
- 2000: ia terlibat dalam pendirian Rumah Pelangi, sebuah kawasan pelestarian dan konservasi hutan (arboretum) milik komunitas Ordo Fratrum Minorum Capuccinorum (OFM Cap).
- 2000-an: ia melakukan penghijauan di Bukit Tunggal (kawasan sekitar Rumah Pelangi) guna menjaga kelestarian hutan.
- 2000-an: ia mendirikan Gereja Katolik Kalvari beserta pondok sederhana, bendungan, sawah, dan lingkar jalan di sekitar bukit.
- Hingga kini, aktivitas di Rumah Pelangi meliputi pendampingan masyarakat sekitar hutan (laki-laki dan perempuan), penanaman buah-buahan dan tanaman langka di lahan kering, serta pelestarian hutan dan rawa.
4. Aleta Baun
Perempuan adat Mollo - Nusa Tenggara Timur
Penerima Goldman Environmental Prize 2013
Menggerakkan masyarakat (laki-laki dan perempuan) untuk memperjuangkan hak-hak adat Mollo yang dilanggar oleh pertambangan marbel di Gunung Mutis, Timor, NTT.
- Sejak kecil, ia kehilangan ibunya dan dirawat oleh orangtua angkat yang mengajarkannya rasa cinta terhadap lingkungan sebagai dasar spiritual.
- 1980-an: Pemda menerbitkan izin operasi perusahan tambang marbel tanpa berkonsultasi dengan warga setempat (laki-laki dan perempuan).
- Saat dewasa, ia mempelopori gerakan melawan perusahaan tambang hingga mendapat ancaman pembunuhan berkali-kali dan harus bersembunyi di tengah hutan bersama bayinya.
- 2000-an: ia menggerakkan 150 perempuan untuk menduduki wilayah perusahaan tambang dengan cara tinggal di atas bebatuan marbel selama 1 tahun.
- 2010: perjuangannya berhasil memaksa perusahaan tambang untuk menghentikan operasinya di wilayah adat Mollo.
5. Rudi Putra
Peneliti biologi - Aceh
Penerima Goldman Environmental Prize 2014
Menggalang dukungan publik nasional dan global melalui media daring untuk melawan perkebunan sawit ilegal di Kawasan Ekosistem Leuser (KEL), Aceh.
- Sejak kecil, ia jatuh cinta pada ilmu biologi dan terlibat aktif dalam pelestarian badak Sumatera.
- Beranjak dewasa, ia menyadari bahwa penghancuran habitat flora dan fauna oleh industri sawit berdampak pada seluruh organisme, termasuk manusia.
- 2006: ia aktif menyuarakan perlindungan lahan, mewakili suara rakyat korban Tsunami.
- 2011: Presiden Indonesia mengeluarkan moratorium sawit, namun deforestasi masih terjadi akibat penebangan ilegal. Sejak itu, Rudi mengawasi tim pemulihan hutan yang menebang pohon sawit di KEL.
- 2013: ia menggalang petisi daring kepada pemerintah Indonesia terkait kebijakan konservasi hingga berhasil meraih dukungan 1,4 juta orang.
- 2014: ia berhasil mengurangi 26 perkebunan sawit ilegal yang 24 diantaranya ditutup atas kesediaan pemiliknya.
6. Petrus Asuy
Tokoh adat Dayak Benuaq - Kalimantan Timur
Penerima Equator Prize (UNDP) 2015
Menggerakkan masyarakat adat Dayak Benuaq (laki-laki dan perempuan) untuk mempertahankan hutan adat yang dilanggar oleh perusahaan sawit.
- 1971: sebuah perusahaan sawit mendapat konsesi dan mulai menggerus hutan adat.
- 1993: salah satu wilayah kecamatan menjadi area konsensi tambang batu bara.
- Sejak 1995, ia menggerakkan komunitas adat Dayak Benuaq (laki-laki dan perempuan) di Muara Tae, Kec. Jempang, Kab. Kutai Barat untuk terus berjuang mempertahankan wilayah hutan adat yang diserobot perusahaan.
- 2015: luas tanah adat tinggal 4.000 hektar, berkurang dari sebelumnya 12.000 hektar pada 1971.
Apa yang bisa kita pelajari?
Bahwa hutan dan lahan adalah warisan alam yang harus kita lestarikan.
Bagaimana caranya?
Melalui penerapan sistem Wilayah Kelola Masyarakat (WKM).
Apa itu WKM?
Tata Kelola Hutan dan Lahan (TKHL) yang melibatkan masyarakat adat dan/atau warga setempat (laki-laki dan perempuan) untuk menentukan kebijakan dalam hal pelestarian lingkungan.
Mengapa masyarakat harus dilibatkan?
Karena masyarakat (laki-laki dan perempuan) memiliki pemahaman dan rasa kepemilikan yang tinggi atas hutan dan lahan yang mereka tinggali secara turun temurun.